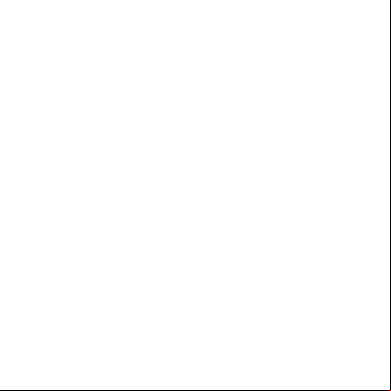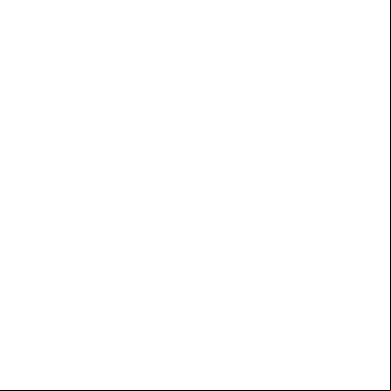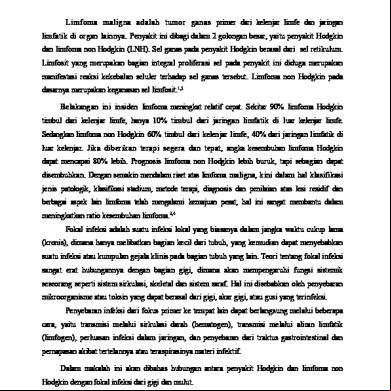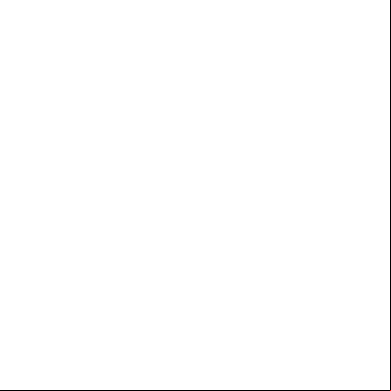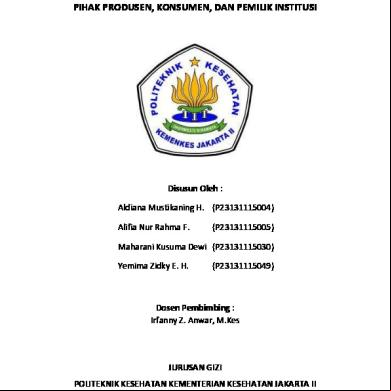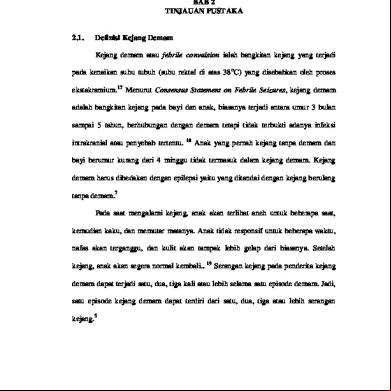Skenario A Kelompok 4 B19 4z431e
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 2z6p3t
Overview 5o1f4z
& View Skenario A Kelompok 4 B19 as PDF for free.
More details 6z3438
- Words: 4,148
- Pages: 21
SKENARIO C Cuka para (blok19) Seorang laki-laki berumur 28 tahun dirujuk ke RSMH Palembang dari RSUD Sekayu sekitar jam 19.00 WIB karena tanpa sengaja meminum air di dalam botol aqua berisi cairan cuka para, penderita mengerang kesakitan di dada dan kesulitan bicara. Pada saat itu, penderita jatuh tertelungkup 2 meter dari rumah panggungnya dan kepalanya terbentur batu. Selama di dalam mobil ambulan, penderita tampak kesakitan berat, gelisah, tidak bisa bicara dan kesulitan bernafas walaupun penderita telah diberikan oksigen. Sekitar jam 23.00 WIB, penderita sampai di Ruang Emergency RSMH Palembang dan diberikan kembali oksigen namun penderita mengalami kesulitan bernafas disertai kesadaran menurun. Pada pemeriksaan fisik : temp aksila 37,0 C, HR 122 x/m, TD 130/90 mmHg, RR 28 x/m dan SpO2 98%. Laki-laki tersebut mengalami disorientasi tempat dan waktu. Pada pemeriksaan pupil isokor diameter 3 mm, reflex cahaya (+), dan tubuhnya banyak mengeluarkan keringat. Auskultasi dada : ronkhi (-), stridor inspirasi (+), ritme jantungnya takikardia regular, abdomen dalam batas normal. Pemeriksaan tambahan Kepala - Hematoma regio frontal, diameter 5 cm -
GCS : 11 E3, M5, V3
-
Edema periorbital dan mukosa mulut
Thoraks - Inspeksi
: retraksi suprasternal, eritema dada
-
Perkusi
: sonor kanan-kiri
-
Auskultasi
: vesicular ronkhi
Abdomen
: dalam batas normal
A. Klarifikasi Istilah
Cuka para
Kesakitan di dada Kesulitan bicara Kesakitan berat Gelisah berlebihan
Kesulitan bernapas Kesadaran menurun
: asam semut/ asam formiat yang biasa digunakan untuk mengkoagulasi karet. : rasa nyeri pada dada : kesulitan dalam mengekspresikan kata : keadaan umum yang terlihat asngat sakit : pengenalan dan aktivitas
motorik
dan tak bertujuan atau kelelahan, biasanya dihubungkan dengan keadaan tegang atau ansietas. : gangguan pada saluran nafas : GCS <14
Disorientasi tempat &waktu: hilangnya tingkah laku yang tepat atau kekacauan mental dalam menenal waktu, tempat atau identitas. Pupil isokor : kesamaan ukuran kedua pupil Ronkhi : suara yang kontinu, terdiri dari suara yang kering, rendah, mirip-dengkur, dari dalam leher atau saluran bronkus akibat obstruksi parsial Stridor inspirasi : suara pernapasan yang bernada tinggi dan kasar Takikardi regular : irama jantung cepat dan merupakan irama sinus Saturasi O2 : ukuran derajat pengikatan oksigen pada hemoglobin, biasa diukur dengan menggunakan oksimeter, yang dinyatakan dalam persentase pembagian kandungan oksigen sebenarnya dengan kapasitas oksigen maksimum dan dikalikan 100 Refleks cahaya : miotik nya pupil jika disinari cahaya Hematoma : pengumpulan darah yang terlokalisasi, umumnya menggumpal, pada organ, rongga, atau jaringan, akibat pecahnya dinding pembuluh darah Region frontal : daerah bagian anterior dari kepala Eritema perioral : bercak merah disekitar mulut Mukosa mulut : jaringan mukosa pada mulut Retraksi suprasternal : tarikan dinding dada pada otot-otot diatas sternum
B. IDENTIFIKASI MASALAH 1. Laki-laki, 28 tahun dirujuk ke RSMH dari RSUD Sekayu dengan keluhan kesakitan di dada dan kesulitan bicara karena meminum cairan cuka para 4 jam yang lalu. 2. Penderita jatuh tertelungkup dari ketinggian 2 meter dari rumah panggungnya dan kepalanya terbentur batu. 3. Di dalam ambulan pasien tampak kesakitan berat, gelisah, tidak dapat bicara, dan kesulitan bernafas walau telah diberi O2. 4. Di UGD RSMH pasien diberi O2 kembali, teyapi tetap kesulitan bernafas juga mengalami penurunan kesadarn. 5. Dari pemeriksaan fisik ditemukan: Temp aksila 37,0 C, HR 122 x/m, TD 130/90 mmHg, RR 28 x/m dan SpO2 98%. Laki-laki tersebut mengalami disorientasi tempat dan waktu. Pada pemeriksaan pupil isokor diameter 3 mm, reflex cahaya (+), dan tubuhnya banyak mengeluarkan keringat. Auskultasi dada : ronkhi (-), stridor inspirasi (+), ritme jantungnya takikardia regular, abdomen dalam batas normal 6. Dari pemeriksaan tambahan ditemukan: Kepala - Hematoma regio frontal, diameter 5 cm
-
GCS : 11 E3, M5, V3
-
Edema periorbital dan mukosa mulut
Thoraks - Inspeksi
: retraksi suprasternal, eritema dada
-
Perkusi
: sonor kanan-kiri
-
Auskultasi
: vesicular ronkhi
Abdomen
: dalam batas normal
C. ANALISIS MASALAH 1. Apa itu Cuka para? Apa dampaknya bila terminum? 2. Bagaimana hubungan terminum cuka para dengan kesakitan dan sulit bicara? 3. Apa dampak jatuh dan kepala terbentur batu pada kasus? 4. Mengapa pasien masih sulit bernapas meski diberi oksigen? 5. Bagaimana pertolongan pertama pada pasien dan apakah pertolongan pertama pada pasien ini sudah tepat? 6. Mengapa kesadaran pasien menurun meski telah diberi oksigen? 7. Bagaimana interpretasi hasil pemeriksaan fisik pada kasus? 8. Bagaimana diagnosis banding? 9. Bagaimana penegakan diagnosis dan diagnosis kerjanya? 10. Bagaimana patogenesis? 11. Bagaimana penatalaksanaan untuk kasus ini? 12. Bagaimana komplikasi, prognosis, dan KUD untuk kasus ini?
D. HIPOTESIS Laki-laki berusia 28 tahun mengalami luka bakar di mulut, gawat napas, dan penurunan kesadaran e.c. intoksikasi cuka para dan trauma kepala
E. SINTESIS 5.1. Identifikasi Cuka Para Cuka para disebut juga asam formiat atau asam semut, merupakan suatu cairan yang tidak berwarna, berbau tajam/menyengat, menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan dan dapat membakar kulit. Efek cuka para/asam formiat terhadap tubuh dapat berupa : Jika terminum (saluran cerna) : membakar traktus digestif, nyeri di faring, batuk, sensasi terbakar, nyeri abdomen, kram abdomen, muntah, diare Jika terinhalasi (saluran nafas) : menyebabkan batuk, sensasi terbakar, sesak nafas, dan tidak sadar Jika terabsorbsi dan masuk peredaran darah : dapat merusak ginjal (albuminuria dan hematuria)
Jika mengenai kulit : nyeri, luka bakar di kulit Jika mengenai mata : nyeri di mata, kemerahan, penglihatan kabur • Bagaimana reaksi cuka para terhadap tubuh? Secara umum, zat asam ketika berkontak dengan sel akan menyebabkan necrosis koagulatif dengan cara denaturasi protein, membentuk koagulum yang disebut eschar. Pembentukan eschar ini memiliki fungsi protektif untuk menghalangi daya tembus zat asam tsb. Asam formiat ini sulit di ekskresikan keluar dari tubuh, akibatnya terjadilah asidosis parah (penurunan pH dibawah 7.37). Adanya penurunan asam atau basa yang hebat dalam darah, menyebabkan sistem pengatur tubuh (sistem dapar darah, respirasi, fungsi ginjal) tidak lagi mampu mengatur pH darah supaya tetap pada nilai pH normal yaitu 7,4. Penurunan pH dibawah 7,20 akan mengakibatkan turunnya volume menit jantung, gangguan ritmus jantung, hipotensi (sampai terjadi syok), gangguan kesadaran dan akhirnya koma. Gejala keracunan pertama akan terlihat setelah periode laten beberapa jam, tanda-tandanya adalah: keluhan sakit kepala, pusing, mual, muntah, gangguan penglihatan menyusul kemudian tidak sadar, dan jika tidak cepat ditangani akan berujung pada kematian. Kalaupun pasien dapat diselamatkan nyawanya, boleh jadi akan mengalami kebutaan, karena telah terjadi kerusakan pada saraf penglihatan (atrofi opticus). Organ pencernaan yang mengalami kerusakan: a.
Bibir bisa terbakar dan tetesan racun bisa mengenai dagu, leher dan dada. Tumpahan racun pada tubuh korban dapat merusak struktur kulit. Pola mulut yang terbakar bisa digunakan untuk melihat racun apa yang diminum. Korban yang meminum racun dengan posisi duduk atau berdiri, racun akan mengalir kedada dan abdomen; bila berbaring, racun akan mengalirti wajah dan pipi lalu keleher belakang. Tumpahan racun bisa masuk kesaluran hidung. b. Bagian inferior mulut bisa terkikis, lidah tertelan atau menciut tergantung bahan racunnya. Faring, laring dan esofagus terkikis dan dalam beberapa menit glotis akan edema. Mukosa saluran nafas bisa rusak dan terjadi adspirasi cairan keparu sehingga terjadi edema paru dan hemoragik. c. Bagian bawah esofagus dan perut mengalami perubahan warna, deskuamasi dan perforasi. Setelah beberapa menit racun bisa mengalir lebih dalam dan dapat merusak usus halus tapi ini jarang terjadi karena faktor waktu dan adanya spasme pilorus. d. Esofagitis Korosif Asam kuat yang tertelan akan menyebabkan nekrosis menggumpal secara histologik dinding esofagus sampai lapisan otot seolah-olah menggumpal. Zat organik (lisol, karbol) menyebabkan edema di mukosa atau sub mukosa. Mukosa terbentuk dari
epitel berlapis gepeng bertingkat yang berlanjut ke faring bagian atas, dalam keadaan normal bersifat alkali dan tidak tahan terhadap isi lambung yang sangat asam. Asam kuat menyebabkan kerusakan pada lambung lebih berat dibandingkan dengan kerusakan di esofagus. Sedangkan basa kuat menimbulkan kerusakan di esofagus lebih berat dari pada lambung. Gejala yang sering timbul adalah disfagia / kesulitan menelan, odinofagia dan adanya rasa sakit retrosternal. Organ pernapasan yg mengalami kerusakan: a. Tumpahan racun bisa masuk kesaluran hidung. Kulit di sekitar hidung terbakar. b. Faring, laring dan esofagus terkikis dan dalam beberapa menit glotis akan edema. Mukosa saluran nafas bisa rusak dan terjadi aspirasi cairan ke paru sehingga terjadi edema paru dan hemoragik. c. Tumpahan racun ke paru bisa menimbulkan edema paru dan bronkopneumonia akibatnya terjadi kematian. Efek lain asam formiat 1. Luka bakar oleh asam penetrasinya tidak lebih dalam daripada alkali sehingga kerusakan yang ditimbulkan umumnya berefek pada permukaan saja. 2. Bagian bawah esofagus dan perut mengalami perubahan warna, deskuamasi dan perforasi. Setelah beberapa menit racun bisa mengalir lebih dalam dan dapat merusak usus halus tapi ini jarang terjadi karena faktor waktu dan adanya spasme pilorus. 3. Bahan-bahan korosive memiliki cara kerja yang berbeda-beda pada jaringan lunak dan dibedakan melalui baunya. Asam kuat bereaksi menyebabkan dehidrasi jaringan, koagulasi protein dan merubah Hb menjadi hematin. 4. Dapat menimbulkan iritasi setempat sebagai akibat reaksi langsung dengan kulit, proses pelarutan atau denaturasi protein pada kulit akibat gangguan keseimbangan membran dan tekanan osmosa pada kulit. Pengaruhnya akan bergantung pada konsentrasi dan lamanya kontak dengan kulit. Pada daerah yang terkena akan terasa panas, terjadi iritasi serta kemerahan, nyeri dan terasa baal. Pembentukan jaringan kulit mati yang berwarna hitam (eschar) - ini sebagian terjadi akibat luka bakar yang diakibatkan oleh bahan asam yang menghasilkan nekrosis koagulasi dengan jalan denaturasi protein. 5. Asam kuat menyebabkan kerusakan pada lambung lebih berat dibandingkan dengan kerusakan di esofagus. Sedangkan basa kuat menimbulkan kerusakan di esofagus lebih berat dari pada lambung.
5.2. Trauma Kepala a.
Klasifikasi trauma kapitis secara umum 1) Simple Head Injury • Ada riwayat trauma kapitis • Tidak pingsan • Gejala sakit kepala dan pusing Umumnya tidak memerlukan perawatan khusus, cukup diberi obat simptomatik dan cukup istirahat.
2) Commotio Cerebri Commotio cerebri (gegar otak) adalah keadaan pingsan yang berlangsung tidak lebih dari 10 menit akibat trauma kepala, yang tidak disertai kerusakan jaringan otak. • Pasien mungkin mengeluh nyeri kepala, vertigo, mungkin muntah dan tampak pucat. • Vertigo dan muntah mungkin disebabkan gegar pada labirin atau terangsangnya pusat-pusat dalam batang otak. • Pada commotio cerebri mungkin pula terdapat amnesia retrograde, yaitu hilangnya ingatan sepanjang masa yang terbatas sebelum terjadinya kecelakaan. Terapi simptomatis, perawatan selama 3-5 hari untuk observasi kemungkinan terjadinya komplikasi dan mobilisasi bertahap. 3) Contusio Cerebri Pada contusio cerebri (memar otak) terjadi perdarahan-perdarahan di dalam jaringan otak tanpa adanya robekan jaringan yang kasat mata, meskipun neuron-neuron mengalami kerusakan atau terputus. Timbulnya lesi contusio di daerah “coup”, “contrecoup”, dan “intermediate” menimbulkan gejala deficit neurologik yang bisa berupa refleks babinsky yang positif dan kelumpuhan UMN. Tekanan darah menjadi rendah dan nadi menjadi lambat, atau menjadi cepat dan lemah. Juga karena pusat vegetatif terlibat, maka rasa mual, muntah dan gangguan pernafasan bisa timbul. Terapi dengan antiserebral edem, simptomatik, neurotropik dan perawatan 7-10 hari. 4) Laceratio Cerebri Dikatakan laceratio cerebri jika kerusakan tersebut disertai dengan robekan piamater. Laceratio biasanya berkaitan dengan adanya perdarahan subaraknoid traumatika, subdural akut, dan intercerebral. Laceratio dapat dibedakan atas laceratio langsung dan tidak langsung. Laceratio langsung disebabkan oleh luka tembus kepala yang disebabkan oleh benda asing atau penetrasi fragmen fraktur terutama pada fraktur depressed terbuka. Sedangkan laceratio tidak langsung disebabkan oleh deformitas jaringan yang hebat akibat kekuatan mekanis. 5) Fracture Basis Cranii Fractur basis cranii bisa mengenai fossa anterior, fossa media, dan fossa posterior. Gejala yang timbul tergantung pada letak atau fossa mana yang terkena. Fraktur pada fossa anterior menimbulkan gejala: • Hematom kacamata tanpa disertai subkonjungtival bleeding • Epistaksis • Rhinorrhoe Fraktur pada fossa media menimbulkan gejala:
• Hematom retroaurikuler, ottorhoe • Perdarahan dari telinga Pemberian antibiotik dosis tinggi untuk mencegah infeksi. Tindakan operatif bila adanya liquorrhoe yang berlangsung lebih dari 6 hari. 6) Hematom Epidural • Letak : antara tulang tengkorak dan duramater • Etiologi : pecahnya a. Meningea media atau cabang-cabangnya • Gejala : setelah terjadi kecelakaan, penderita pingsan atau hanya nyeri kepala sebentar kemudian membaik dengan sendirinya tetapi beberapa jam kemudian timbul gejala-gejala yang memperberat progresif seperti nyeri kepala, pusing, kesadaran menurun, nadi melambat, tekanan darah meninggi, pupil pada sisi perdarahan mula-mula sempit, lalu menjadi lebar, dan akhirnya tidak bereaksi terhadap refleks cahaya. Ini adalah tanda-tanda bahwa sudah terjadi herniasi tentorial. • Akut (minimal 24jam sampai dengan 3x24 jam) • Pada pemeriksaan kepala mungkin pada salah satu sisi kepala didapati hematoma subkutan • Pemeriksaan neurologis menunjukkan pada sisi hematom pupil melebar. Pada sisi kontralateral dari hematom, dapat dijumpai tandatanda kerusakan traktus piramidalis, misalnya : hemiparesis, refleks tendon meninggi, dan refleks patologik positif. • Penatalaksanaannya yaitu tindakan evakuasi darah (dekompresi) dan pengikatan pembuluh darah. 7) Hematom subdural • Letak : di bawah duramater • Etiologi : pecahnya bridging vein, gabungan robekan bridging veins dan laserasi piamater serta arachnoid dari kortex cerebri • Gejala subakut : mirip epidural hematom, timbul dalam 3 hari pertama • Kronis : 3 minggu atau berbulan-bulan setelah trauma • Operasi sebaiknya segera dilakukan untuk mengurangi tekanan dalam otak (dekompresi) dengan melakukan evakuasi hematom. Penanganan subdural hematom akut terdiri dari trepanasi-dekompresi.
8) Perdarahan Intraserebral Perdarahan dalam cortex cerebri yang berasal dari arteri kortikal, terbanyak pada lobus temporalis. Perdarahan intraserebral akibat trauma kapitis yang berupa hematom hanya berupa perdarahan kecil-kecil saja. Jika penderita dengan perdarahan intraserebral luput dari kematian, perdarahannya akan direorganisasi dengan pembentukan gliosis dan kavitasi. Keadaan ini bisa menimbulkan manifestasi neurologik sesuai dengan fungsi bagian otak yang terkena.
b. Penilaian Trauma Kepala Beratnya trauma deselerasi yang dialami korban tergantung pada beberapa hal, yaitu: •
Kemampuan dari obyek statis yang ditubruk untuk menahan tubuh
•
Karakteristik dari obyek tersebut batu (keras, mungkin tidak teratur)
•
Elastisitas dan viskositas jaringan tubuh kepala tidak bersifat elastic; otak bisa menyerap energy kinetik akibat benturan
•
Posisi dari tubuh relative terhadap permukaan benturan tertelungkup, kepala membentur batu Penilaian trauma (berat , sedang, ringan) Jenis pemeriksaan Respon buka mata (eye opening / E) :
Nilai
Spontan
4
Terhadap suara
3
Terhadap nyeri
2
Tidak ada Respon motorik terbaik (M) :
1
Ikut perintah
6
Melokalisir nyeri
5
Fleksi normal (menarik anggota yang
4
dirangsang)
3
Fleksi abnormal (dekortikasi)
2
Ekstensi abnormal (deserebrasi)
1
Tidak ada (flasid) Respon verbal (V) : Berorientasi baik
5
Berbicara mengacau (bingung)
4
Kata-kata tidak teratur
3
Suara tidak jelas
2
Tidak ada
1
GCS 11
: penurunan kesadaran sedang
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korban kemungkina besar hanya mengalami trauma kepala dengan dugaan sebagai berikut: •
Pecahnya pembuluh darah di region frontal kepala (di dahi) akibat terbentur langsung dengan batu sehingga menimbulkan hematoma berukuran 5 cm.
•
Mungkin hanya terdapat komosio serebri (walau korban tidak pingsan) GCS 13-15 (cedera kepala ringan) Dari hasil pemeriksaan pupil (setelah sekitar 4 jam sejak kejadian) tidak didapatkan gejala lateralisasi maupun gejala peningkatan intracranial lain seperti nyeri kepala, mual dan muntah sehingga kemungkinan adanya peningkatan intracranial akibat perdarahan intracranial/kontusio atau edema otak sangat kecil
•
Otak mungkin saja mengalami cedera coup maupun contra-coup Berdasarkan dugaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa GCS korban yang
termasuk ke dalam cedera kepala sedang (9-13) bukan disebabkan oleh trauma kepala yang dialaminya, melainkan cenderung karena intoksikasi zat korosif. Meski hasil pemeriksaan di RSMH hanya menyimpulkan adanya trauma kepala, harus tetap dicurigai adanya fraktur servikal yang perlu dipastikan dengan foto polos leher. Mungkin korban mengalami ekstensi leher yang dapat menyebabkan fraktur akibat dahi yang terbentur batu sedangkan tubuhnya berada dalam posisi tertelungkup.
Mengapa pada kasus terjadi hematom hanya pada region frontal? Karena ia jatuh tertelungkup berarti bagian frontal kepala di bawah.
Bagaimana pembentukan hematomnya?
c. Dampak Trauma Kepala Ketinggian 2 meter tidak terlalu menyebabkan cedera yang parah, diperjelas juga dengan pemeriksaan pupil yang isokor dengan diameter 3 mm dan refleks cahaya +, tetapi kita harus tetap melakukan pemeriksaan kepala (CT Scan atau foto polos kepala) mengingat GCS nya 11 (untuk mengetahui apakah penyebabnya karena adanya cedera kepala sedang atau kekurangan oksigen). Penatalaksanaan awal jika korban mengalami cedera kepala : •
Dekompresi dengan trepanasi sederhana
•
Kompres dengan air dingin
Dari skenario tidak didapatkan data mengenai pertolongan pertama untuk trauma kepala yang di alami pasien, hal ini yang akan mengakibatkan trauma kepala yang dialami pasien dapat menyebabkan komplikasi berupa penurunan kesadaran
5.3. Interpretasi Hasil Pemeriksaan Fisik
Temperatur aksila 37OC Normal 36,5-37,5 OC
Tidak ada gangguan dalam termoregulasi
HR 122x/m Takikardia, akibat pengaktifan saraf simpatis sebagai kompensasi tubuh untuk memenuhi kekurangan O2 akibat penyempitan saluran nafas
TD 130/90 mmHg meningkat Terjadi vasokontriksi akibat kinerja simpatis dan juga penambahan CO akibat peningkatan frekuensi kontraksi jantung
RR 28 x/mnt Meningkat kompensasi tubuh untuk memenuhi kekurangan O2 akibat penyempitan saluran nafas
SpO2 98% Normal (> 95 %)
Disorientasi tempat dan waktu Tidak normal Terjadi penurunan kesadaran Kemungkinan : 1. karena trauma kapitis yang dialaminya yang mengenai daerah frontal,namun perlu pemeriksaan lebih lanjut yakni CT scan. 2. penurunan O2 ke otak.
Pupil isokor diameter 3 mm Normal ,3-5 mm tidak ada lateralisasi
Reflex cahaya + Reflex pupil normal,tidak ada penekanan pada saraf cranial ke 3
Tubuh banyak mengeluarkan keringat Terjadi akibat aktivasi simpatis
Auskultasi dada •
Ronkhi (-)
Normal Tidak ada penumpukan cairan di paru •
Stridor inspirasi (+) Terjadi akibat penyempitan saluran nafas
Ritme jantung takikardi regular kompensasi tubuh untuk memenuhi kekurangan O2 akibat penyempitan saluran nafas
Abdomen dalam batas normal Tidak ada gangguan dalam abdomennya Kemungkinan cairan cuka para belum mengenai area lambung,namun masih sebatas area esophagus
Interpretasi Data Tambahan Hematom regio frontal d=5 cm o ruptur/ pecah pembuluh darah di bagian frontal karena terjatuh dari ketinggian 2 m akumulasi darah di daerah frontal hematoma eritem perioral, dan mukosa mulut o Cuka para (zat korosif) kerusakan pada saluran cerna atas iritasi area perioral (minum dari botol) panas vasodilatasi pembuluh darah dan arteriole kerusakan jaringan pelepasan mediator inflamasi (histamin, bradikinin, serotinin) peningkatan permeabilitas vaskular eritema perioral dan mukosa mulut. retraksi suprasternal o zat korosif dari sal cerna teraspirasi ke saluran pernapasan/ perforasi langsung di esofagus ke laring dan trakea edema mukosa laring obstruksi jalan nafas penurunan aliran udara ke alveolus mekanisme kompensasi untuk mempertahankan ventilasi alveolus penggunaan otot-otot bantu nafas retraksi dinding dada.
bercak eritem dada cuka para tertumpah ke dada iritasi di kulit merusak lapisan kulit eritem dada
5.4. Penegakan Diagnosis Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sudah tertera dalam kasus. Berdasarkan inilah pasien didiagnosis mengalami intoksikasi cuka para dan trauma kepala.
5.5. Patogenesis
5.6. Penatalaksanaan a. Penanganan Awal yang Seharusnya Diberikan di RSUD Sekayu Lakukan Prinsip penanganan pasien gawat darurat: -
Periksa Airway pasien kesulitan bicara (stridor?) buka mulut pasien, bebaskan jalan napas, pasang orofaringeal airway.
-
Periksa Breathing hitung RR pasien, alirkan oksigen melalui orofaringeal airway. Jika breathing tidak membaik, pasang airway definitive, endotracheal tube.
-
Periksa Circulation pasien takikardi reguler, TD 130/90 mmHg, prevensi shock cairan RL 2L.
-
Periksa Disability GCS ketika di RSUD diduga sekitar 14-15, dengan adanya benturan di region frontal, monitor pasien dengan ketat dan segera lakukan CT Scan.
-
Periksa Exposure o Kepala : hematom (d=5) region frontal, eritema perioral dan mukosa mulut o Toraks: jejas (-), eritema (+) o Abdomen: normal o Periksa bagian ekstremitas Bersihkan sisa-sisa cuka para pada perioral dan dada, alirkan cairan (250500 ml). jika terdapat gangguan jalan napas, pemberian susu atau air merupakan kontraindikasi (susu akan mengganggu proses edoskopi, asam sulfat yang dilarutkan dengan air akan menghasilkan panas). Jangan lakukan netralisasi, karena akan menghasilkan panas akibat reaksi eksotermal dari proses netralisasi. Lakukan pemeriksaan endoskopi (dahulukan CT Scan)
-
Pastikan ABC pasien stabil, dan siap dirujuk ke RSMH, monitor vital sign pasien selama perjalanan
b.Penatalaksanaan untuk intoksikasi zat korosif (cuka para) : 1. Pertolongan pertama •
Indentifikasi agen korosif yang tertelan
•
Hindari : -
Penggunaan emetik : sebabkan pajanan berulang
-
Agen penetralisasi : sebabkan injuri termal
-
Bilas lambung : sebabkan perforasi
-
Pertimbangkan NGT
2. Perawatan intensif di UGD :
•
Diprioritaskan – jalur napas dan tanda vital, monitoring jantung segera dan akses intravena.
•
Kontrol jalur napas o
Karena resiko yang sangat cepat dari edema jalur napas, evakuasi segera jalur napas dan kondisi kesadaran. Persiapkan segera alat intubasi endotrakeal dan krikotirotomi. Intubasi orotrakeal atau intubasi dengan bantuan optik fiber lebih baik daripada nasotrakeal untuk mencegah perforasi jaringan lunak
o
Sebisanya, hindari induksi paralisis saat intubasi karena resiko dari distorsi anatomi akibat perdarahan dan nekrosis.
o
Krikotirotomi atau percutaneous needle cricothyrotomy penting dilakukan bila didapat tanda friabilitas ekstrem jaringan atau edema yang signifikan.
•
Pengosongan lambung dan dekontaminasi : o Jangan diberi obat perangsang muntah, cegah re-eksposur dengan agen kaustil o Gastric lavage o NGT suction – spasme dari spingter pilorik mencegah terpaparnya agen terhadap mukosa gaster sampai 90 menit – mencegah terpaparnya intestinal
•
Pemberian cairan intravena.
3. Medikamentosa •
Terapi if
•
Penggunaan kortikosteroid . masih kontroversial, beberapa studi membuktikan efektivitasnya dalam pencegahan striktur. Seperti, metil prednisolon 40-60 mg/hari IV, diberikan setidaknya 3 minggu
•
Antibiotik. Diberikan pada pasien yang menerima terapi steroid di atas. -
Antibiotik – sefalosporin (ceftriaxone) 1-2 gram IV per 24 jam, tidak melebihi 4 g/hari
-
Antibiotik – penisilin dan Beta-lactamase Inhibitor – jika terjadi perforasi
•
PPI – proton pump inhibitor – mencegah terpajannya esofagus yang terluka terhadap asam lambung, yang dapat menyebabkan striktura esofagus
•
Pantoprazole – terapi untuk GER dan esofagitis erosif.
•
Analgesik parenteral, monitor tanda sedasi dan depresi dari respirasi.
4. Follow up •
Pasien yang tidak sengaja tertelan agen penyebab yang asimtomatik dan tidak menunjukkan gejala apapun, boleh dipulangkan 2-4 jam setelah observasi, tak ada kelainan anatomi, pasien harus bisa meminum cairan tanpa kesulitan, tak ada gangguan berbicara
•
NPO (nothing per mouth)
•
Esofagram setelah 3-4 minggu
5. Terapi nutrisi (intake makanan) •
Prinsip : NPO (nothing per mouth) – jangan berikan apapun peroral
•
FEEDING tube o Alat kedokteran yang digunakan untuk pemberian makanan, dikarenakan pasien tidak dapat mengkonsumsi makanan dengan mengunyah o Dinamakan enteral feeding / tube feeding
•
Tipe enteral feeding : o Nasogastrik – dengan selang nasogastrik (nares – esofagus – lambung) o Gastric feeding tube – insersi melalui insisi di abdomen ke lambung (digunakan untuk pemasukan nutrisi enteral jangka panjang. Tipe paling umum adalah percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) tube
•
Efektivitas Dapat digunakan untuk bolus ataupun pemberian makan terus menerus
6. Yang perlu diperhatikan (yang SALAH) : •
Gagal mengevaluasi dan pertolongan jalur napas yang agresif
•
Upaya menetralkan zat yang tertelan dengan asam atau basa lemah
•
Menginduksi muntah – karena dapat membuat esofagus terpajan ulang dengan bahan
•
Asumsi bahwa tidak adanya luka bakar pada orofaring akan menyingkirkan kerusakan jaringan distal
•
Gagal dalam memperoleh data zat/bahan yang tertelan
•
Tidak segera merujuk ke dokter spesialis gastrointestinal / bedah digestif
c. Penatalaksanaan trauma kepala a. Cedera Kepala Ringan (GCS 14-15) •
Riwayat : i. Nama, umur, jenis kelamin, ras, pekerjaan ii. Mekanisme cedera iii. Waktu cedera iv. Tidak sadar segera setelah cedera v. Tingkat kewaspadaan vi. Amnesia : Retrograde, Antegrade vii. Sakit kepala : ringan, sedang, berat
•
Pemeriksaan umum untuk menyingkirkan cedera sistemik
•
Pemeriksaan neurologis terbatas
•
Pemeriksaan rontgen vertebra servikal dan lainnya sesuai indikasi
•
Pemeriksaan CT scan kepala sangat ideal pada setiap penderita kecuali bila memang sama sekali asimtomatik dan pemeriksaan neurologis normal
•
Observasi atau dirawat di RS jika : i. CT scan tidak ada ii. CT scan abnormal iii. Semua cedera tembus iv. Riwayat hilang kesadaran v. Kesadaran menurun vi. Sakit kepala sedang- berat vii. Intoksikasi alcohol/obat-obatan viii. Kebocoran likuor : Rhinorea-otorea ix. Cedera penyerta yang bermakna x. Tak ada keluarga di rumah xi. GCS < 15 xii. Defisit neurologis fokal
b. Cedera Kepala Sedang (GCS 9-13) •
Sama dengan untuk cedera kepala ringan ditambah pemeriksaan darah sederhana
•
Pemeriksaan CT scan kepala pada semua kasus
•
Setelah dirawat : i. Pemeriksaan neurologis periodic
ii. Pemeriksaan CT scan ulang bila kondisi penderita memburuk atau bila penderita akan dipulangkan c. Cedera Kepala Berat (GCS <8) •
Periksa ABCDE
•
Primary Survey dan resusitasi
•
Secondary Survey dan riwayat AMPLE
•
Reevaluasi neurologis : GCS i. Respon buka mata ii. Respon motorik iii. Respon verbal iv. Respon cahaya pupil
•
Obat-obatan : i. Manitol ii. Hiperventilasi sedang (PCO2 <35mmHg) iii. Antikonvulsan
•
Tes Diagnostik (sesuai urutan): i. CT scan ii. Ventrikulografi udara iii. Angiogram
5.7. Komplikasi dan Prognosis 1. Prognosis
Dubia. Tergantung dari derajat kerusakan jaringan, lama waktu terpajan dan sifat fisik dari agen (termasuk pH, volume, dan konsentrasi; kemampuan penetrasi jaringan, dan titration reserve (jumlah jaringan yang dibutuhkan untuk menetralisir agen) 2. Komplikasi
Edema jalan napas atau obstruksi
Striktur esofagus
Perforasi dari gastroesofagus o Komplikasi sekundernya termasuk : mediastinitis, perikarditis, pleuritis, pembentukan fistula trakeoesofagal, pembentukan fistula esofagal-aortic, dan peritonitis o Perforasi dapat terjadi 4 hari setelah terpapar zat asam. o Obstruksi dari saluran gaster setelah 3-4 minggu terpajan o Hemorhagik pada regio gastrointestinal secara akut o Perdarahan dari traktus gastrointestinal
Resiko jangka panjang, squamous cell carcinoma, ca esofagus 1-4% kasus.
3. Kompetensi Dokter Umum Kompetensi dokter umum untuk trauma kepala dan keracunan adalah 3B, yaitu mampu membuat diagnosis berdasarkan pemeriksaan fisik dan tambahan, dapat memutuskan dan memberikan terapi awal, serta merujuk ke spesialis yang relevan pada kasus gawat darurat. Untuk kasus Gawat darurat (dalam kasus ini), dokter rumah sakit harus melakukan tatalaksana sampai kondisi pasien stabil
GCS : 11 E3, M5, V3
-
Edema periorbital dan mukosa mulut
Thoraks - Inspeksi
: retraksi suprasternal, eritema dada
-
Perkusi
: sonor kanan-kiri
-
Auskultasi
: vesicular ronkhi
Abdomen
: dalam batas normal
A. Klarifikasi Istilah
Cuka para
Kesakitan di dada Kesulitan bicara Kesakitan berat Gelisah berlebihan
Kesulitan bernapas Kesadaran menurun
: asam semut/ asam formiat yang biasa digunakan untuk mengkoagulasi karet. : rasa nyeri pada dada : kesulitan dalam mengekspresikan kata : keadaan umum yang terlihat asngat sakit : pengenalan dan aktivitas
motorik
dan tak bertujuan atau kelelahan, biasanya dihubungkan dengan keadaan tegang atau ansietas. : gangguan pada saluran nafas : GCS <14
Disorientasi tempat &waktu: hilangnya tingkah laku yang tepat atau kekacauan mental dalam menenal waktu, tempat atau identitas. Pupil isokor : kesamaan ukuran kedua pupil Ronkhi : suara yang kontinu, terdiri dari suara yang kering, rendah, mirip-dengkur, dari dalam leher atau saluran bronkus akibat obstruksi parsial Stridor inspirasi : suara pernapasan yang bernada tinggi dan kasar Takikardi regular : irama jantung cepat dan merupakan irama sinus Saturasi O2 : ukuran derajat pengikatan oksigen pada hemoglobin, biasa diukur dengan menggunakan oksimeter, yang dinyatakan dalam persentase pembagian kandungan oksigen sebenarnya dengan kapasitas oksigen maksimum dan dikalikan 100 Refleks cahaya : miotik nya pupil jika disinari cahaya Hematoma : pengumpulan darah yang terlokalisasi, umumnya menggumpal, pada organ, rongga, atau jaringan, akibat pecahnya dinding pembuluh darah Region frontal : daerah bagian anterior dari kepala Eritema perioral : bercak merah disekitar mulut Mukosa mulut : jaringan mukosa pada mulut Retraksi suprasternal : tarikan dinding dada pada otot-otot diatas sternum
B. IDENTIFIKASI MASALAH 1. Laki-laki, 28 tahun dirujuk ke RSMH dari RSUD Sekayu dengan keluhan kesakitan di dada dan kesulitan bicara karena meminum cairan cuka para 4 jam yang lalu. 2. Penderita jatuh tertelungkup dari ketinggian 2 meter dari rumah panggungnya dan kepalanya terbentur batu. 3. Di dalam ambulan pasien tampak kesakitan berat, gelisah, tidak dapat bicara, dan kesulitan bernafas walau telah diberi O2. 4. Di UGD RSMH pasien diberi O2 kembali, teyapi tetap kesulitan bernafas juga mengalami penurunan kesadarn. 5. Dari pemeriksaan fisik ditemukan: Temp aksila 37,0 C, HR 122 x/m, TD 130/90 mmHg, RR 28 x/m dan SpO2 98%. Laki-laki tersebut mengalami disorientasi tempat dan waktu. Pada pemeriksaan pupil isokor diameter 3 mm, reflex cahaya (+), dan tubuhnya banyak mengeluarkan keringat. Auskultasi dada : ronkhi (-), stridor inspirasi (+), ritme jantungnya takikardia regular, abdomen dalam batas normal 6. Dari pemeriksaan tambahan ditemukan: Kepala - Hematoma regio frontal, diameter 5 cm
-
GCS : 11 E3, M5, V3
-
Edema periorbital dan mukosa mulut
Thoraks - Inspeksi
: retraksi suprasternal, eritema dada
-
Perkusi
: sonor kanan-kiri
-
Auskultasi
: vesicular ronkhi
Abdomen
: dalam batas normal
C. ANALISIS MASALAH 1. Apa itu Cuka para? Apa dampaknya bila terminum? 2. Bagaimana hubungan terminum cuka para dengan kesakitan dan sulit bicara? 3. Apa dampak jatuh dan kepala terbentur batu pada kasus? 4. Mengapa pasien masih sulit bernapas meski diberi oksigen? 5. Bagaimana pertolongan pertama pada pasien dan apakah pertolongan pertama pada pasien ini sudah tepat? 6. Mengapa kesadaran pasien menurun meski telah diberi oksigen? 7. Bagaimana interpretasi hasil pemeriksaan fisik pada kasus? 8. Bagaimana diagnosis banding? 9. Bagaimana penegakan diagnosis dan diagnosis kerjanya? 10. Bagaimana patogenesis? 11. Bagaimana penatalaksanaan untuk kasus ini? 12. Bagaimana komplikasi, prognosis, dan KUD untuk kasus ini?
D. HIPOTESIS Laki-laki berusia 28 tahun mengalami luka bakar di mulut, gawat napas, dan penurunan kesadaran e.c. intoksikasi cuka para dan trauma kepala
E. SINTESIS 5.1. Identifikasi Cuka Para Cuka para disebut juga asam formiat atau asam semut, merupakan suatu cairan yang tidak berwarna, berbau tajam/menyengat, menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan dan dapat membakar kulit. Efek cuka para/asam formiat terhadap tubuh dapat berupa : Jika terminum (saluran cerna) : membakar traktus digestif, nyeri di faring, batuk, sensasi terbakar, nyeri abdomen, kram abdomen, muntah, diare Jika terinhalasi (saluran nafas) : menyebabkan batuk, sensasi terbakar, sesak nafas, dan tidak sadar Jika terabsorbsi dan masuk peredaran darah : dapat merusak ginjal (albuminuria dan hematuria)
Jika mengenai kulit : nyeri, luka bakar di kulit Jika mengenai mata : nyeri di mata, kemerahan, penglihatan kabur • Bagaimana reaksi cuka para terhadap tubuh? Secara umum, zat asam ketika berkontak dengan sel akan menyebabkan necrosis koagulatif dengan cara denaturasi protein, membentuk koagulum yang disebut eschar. Pembentukan eschar ini memiliki fungsi protektif untuk menghalangi daya tembus zat asam tsb. Asam formiat ini sulit di ekskresikan keluar dari tubuh, akibatnya terjadilah asidosis parah (penurunan pH dibawah 7.37). Adanya penurunan asam atau basa yang hebat dalam darah, menyebabkan sistem pengatur tubuh (sistem dapar darah, respirasi, fungsi ginjal) tidak lagi mampu mengatur pH darah supaya tetap pada nilai pH normal yaitu 7,4. Penurunan pH dibawah 7,20 akan mengakibatkan turunnya volume menit jantung, gangguan ritmus jantung, hipotensi (sampai terjadi syok), gangguan kesadaran dan akhirnya koma. Gejala keracunan pertama akan terlihat setelah periode laten beberapa jam, tanda-tandanya adalah: keluhan sakit kepala, pusing, mual, muntah, gangguan penglihatan menyusul kemudian tidak sadar, dan jika tidak cepat ditangani akan berujung pada kematian. Kalaupun pasien dapat diselamatkan nyawanya, boleh jadi akan mengalami kebutaan, karena telah terjadi kerusakan pada saraf penglihatan (atrofi opticus). Organ pencernaan yang mengalami kerusakan: a.
Bibir bisa terbakar dan tetesan racun bisa mengenai dagu, leher dan dada. Tumpahan racun pada tubuh korban dapat merusak struktur kulit. Pola mulut yang terbakar bisa digunakan untuk melihat racun apa yang diminum. Korban yang meminum racun dengan posisi duduk atau berdiri, racun akan mengalir kedada dan abdomen; bila berbaring, racun akan mengalirti wajah dan pipi lalu keleher belakang. Tumpahan racun bisa masuk kesaluran hidung. b. Bagian inferior mulut bisa terkikis, lidah tertelan atau menciut tergantung bahan racunnya. Faring, laring dan esofagus terkikis dan dalam beberapa menit glotis akan edema. Mukosa saluran nafas bisa rusak dan terjadi adspirasi cairan keparu sehingga terjadi edema paru dan hemoragik. c. Bagian bawah esofagus dan perut mengalami perubahan warna, deskuamasi dan perforasi. Setelah beberapa menit racun bisa mengalir lebih dalam dan dapat merusak usus halus tapi ini jarang terjadi karena faktor waktu dan adanya spasme pilorus. d. Esofagitis Korosif Asam kuat yang tertelan akan menyebabkan nekrosis menggumpal secara histologik dinding esofagus sampai lapisan otot seolah-olah menggumpal. Zat organik (lisol, karbol) menyebabkan edema di mukosa atau sub mukosa. Mukosa terbentuk dari
epitel berlapis gepeng bertingkat yang berlanjut ke faring bagian atas, dalam keadaan normal bersifat alkali dan tidak tahan terhadap isi lambung yang sangat asam. Asam kuat menyebabkan kerusakan pada lambung lebih berat dibandingkan dengan kerusakan di esofagus. Sedangkan basa kuat menimbulkan kerusakan di esofagus lebih berat dari pada lambung. Gejala yang sering timbul adalah disfagia / kesulitan menelan, odinofagia dan adanya rasa sakit retrosternal. Organ pernapasan yg mengalami kerusakan: a. Tumpahan racun bisa masuk kesaluran hidung. Kulit di sekitar hidung terbakar. b. Faring, laring dan esofagus terkikis dan dalam beberapa menit glotis akan edema. Mukosa saluran nafas bisa rusak dan terjadi aspirasi cairan ke paru sehingga terjadi edema paru dan hemoragik. c. Tumpahan racun ke paru bisa menimbulkan edema paru dan bronkopneumonia akibatnya terjadi kematian. Efek lain asam formiat 1. Luka bakar oleh asam penetrasinya tidak lebih dalam daripada alkali sehingga kerusakan yang ditimbulkan umumnya berefek pada permukaan saja. 2. Bagian bawah esofagus dan perut mengalami perubahan warna, deskuamasi dan perforasi. Setelah beberapa menit racun bisa mengalir lebih dalam dan dapat merusak usus halus tapi ini jarang terjadi karena faktor waktu dan adanya spasme pilorus. 3. Bahan-bahan korosive memiliki cara kerja yang berbeda-beda pada jaringan lunak dan dibedakan melalui baunya. Asam kuat bereaksi menyebabkan dehidrasi jaringan, koagulasi protein dan merubah Hb menjadi hematin. 4. Dapat menimbulkan iritasi setempat sebagai akibat reaksi langsung dengan kulit, proses pelarutan atau denaturasi protein pada kulit akibat gangguan keseimbangan membran dan tekanan osmosa pada kulit. Pengaruhnya akan bergantung pada konsentrasi dan lamanya kontak dengan kulit. Pada daerah yang terkena akan terasa panas, terjadi iritasi serta kemerahan, nyeri dan terasa baal. Pembentukan jaringan kulit mati yang berwarna hitam (eschar) - ini sebagian terjadi akibat luka bakar yang diakibatkan oleh bahan asam yang menghasilkan nekrosis koagulasi dengan jalan denaturasi protein. 5. Asam kuat menyebabkan kerusakan pada lambung lebih berat dibandingkan dengan kerusakan di esofagus. Sedangkan basa kuat menimbulkan kerusakan di esofagus lebih berat dari pada lambung.
5.2. Trauma Kepala a.
Klasifikasi trauma kapitis secara umum 1) Simple Head Injury • Ada riwayat trauma kapitis • Tidak pingsan • Gejala sakit kepala dan pusing Umumnya tidak memerlukan perawatan khusus, cukup diberi obat simptomatik dan cukup istirahat.
2) Commotio Cerebri Commotio cerebri (gegar otak) adalah keadaan pingsan yang berlangsung tidak lebih dari 10 menit akibat trauma kepala, yang tidak disertai kerusakan jaringan otak. • Pasien mungkin mengeluh nyeri kepala, vertigo, mungkin muntah dan tampak pucat. • Vertigo dan muntah mungkin disebabkan gegar pada labirin atau terangsangnya pusat-pusat dalam batang otak. • Pada commotio cerebri mungkin pula terdapat amnesia retrograde, yaitu hilangnya ingatan sepanjang masa yang terbatas sebelum terjadinya kecelakaan. Terapi simptomatis, perawatan selama 3-5 hari untuk observasi kemungkinan terjadinya komplikasi dan mobilisasi bertahap. 3) Contusio Cerebri Pada contusio cerebri (memar otak) terjadi perdarahan-perdarahan di dalam jaringan otak tanpa adanya robekan jaringan yang kasat mata, meskipun neuron-neuron mengalami kerusakan atau terputus. Timbulnya lesi contusio di daerah “coup”, “contrecoup”, dan “intermediate” menimbulkan gejala deficit neurologik yang bisa berupa refleks babinsky yang positif dan kelumpuhan UMN. Tekanan darah menjadi rendah dan nadi menjadi lambat, atau menjadi cepat dan lemah. Juga karena pusat vegetatif terlibat, maka rasa mual, muntah dan gangguan pernafasan bisa timbul. Terapi dengan antiserebral edem, simptomatik, neurotropik dan perawatan 7-10 hari. 4) Laceratio Cerebri Dikatakan laceratio cerebri jika kerusakan tersebut disertai dengan robekan piamater. Laceratio biasanya berkaitan dengan adanya perdarahan subaraknoid traumatika, subdural akut, dan intercerebral. Laceratio dapat dibedakan atas laceratio langsung dan tidak langsung. Laceratio langsung disebabkan oleh luka tembus kepala yang disebabkan oleh benda asing atau penetrasi fragmen fraktur terutama pada fraktur depressed terbuka. Sedangkan laceratio tidak langsung disebabkan oleh deformitas jaringan yang hebat akibat kekuatan mekanis. 5) Fracture Basis Cranii Fractur basis cranii bisa mengenai fossa anterior, fossa media, dan fossa posterior. Gejala yang timbul tergantung pada letak atau fossa mana yang terkena. Fraktur pada fossa anterior menimbulkan gejala: • Hematom kacamata tanpa disertai subkonjungtival bleeding • Epistaksis • Rhinorrhoe Fraktur pada fossa media menimbulkan gejala:
• Hematom retroaurikuler, ottorhoe • Perdarahan dari telinga Pemberian antibiotik dosis tinggi untuk mencegah infeksi. Tindakan operatif bila adanya liquorrhoe yang berlangsung lebih dari 6 hari. 6) Hematom Epidural • Letak : antara tulang tengkorak dan duramater • Etiologi : pecahnya a. Meningea media atau cabang-cabangnya • Gejala : setelah terjadi kecelakaan, penderita pingsan atau hanya nyeri kepala sebentar kemudian membaik dengan sendirinya tetapi beberapa jam kemudian timbul gejala-gejala yang memperberat progresif seperti nyeri kepala, pusing, kesadaran menurun, nadi melambat, tekanan darah meninggi, pupil pada sisi perdarahan mula-mula sempit, lalu menjadi lebar, dan akhirnya tidak bereaksi terhadap refleks cahaya. Ini adalah tanda-tanda bahwa sudah terjadi herniasi tentorial. • Akut (minimal 24jam sampai dengan 3x24 jam) • Pada pemeriksaan kepala mungkin pada salah satu sisi kepala didapati hematoma subkutan • Pemeriksaan neurologis menunjukkan pada sisi hematom pupil melebar. Pada sisi kontralateral dari hematom, dapat dijumpai tandatanda kerusakan traktus piramidalis, misalnya : hemiparesis, refleks tendon meninggi, dan refleks patologik positif. • Penatalaksanaannya yaitu tindakan evakuasi darah (dekompresi) dan pengikatan pembuluh darah. 7) Hematom subdural • Letak : di bawah duramater • Etiologi : pecahnya bridging vein, gabungan robekan bridging veins dan laserasi piamater serta arachnoid dari kortex cerebri • Gejala subakut : mirip epidural hematom, timbul dalam 3 hari pertama • Kronis : 3 minggu atau berbulan-bulan setelah trauma • Operasi sebaiknya segera dilakukan untuk mengurangi tekanan dalam otak (dekompresi) dengan melakukan evakuasi hematom. Penanganan subdural hematom akut terdiri dari trepanasi-dekompresi.
8) Perdarahan Intraserebral Perdarahan dalam cortex cerebri yang berasal dari arteri kortikal, terbanyak pada lobus temporalis. Perdarahan intraserebral akibat trauma kapitis yang berupa hematom hanya berupa perdarahan kecil-kecil saja. Jika penderita dengan perdarahan intraserebral luput dari kematian, perdarahannya akan direorganisasi dengan pembentukan gliosis dan kavitasi. Keadaan ini bisa menimbulkan manifestasi neurologik sesuai dengan fungsi bagian otak yang terkena.
b. Penilaian Trauma Kepala Beratnya trauma deselerasi yang dialami korban tergantung pada beberapa hal, yaitu: •
Kemampuan dari obyek statis yang ditubruk untuk menahan tubuh
•
Karakteristik dari obyek tersebut batu (keras, mungkin tidak teratur)
•
Elastisitas dan viskositas jaringan tubuh kepala tidak bersifat elastic; otak bisa menyerap energy kinetik akibat benturan
•
Posisi dari tubuh relative terhadap permukaan benturan tertelungkup, kepala membentur batu Penilaian trauma (berat , sedang, ringan) Jenis pemeriksaan Respon buka mata (eye opening / E) :
Nilai
Spontan
4
Terhadap suara
3
Terhadap nyeri
2
Tidak ada Respon motorik terbaik (M) :
1
Ikut perintah
6
Melokalisir nyeri
5
Fleksi normal (menarik anggota yang
4
dirangsang)
3
Fleksi abnormal (dekortikasi)
2
Ekstensi abnormal (deserebrasi)
1
Tidak ada (flasid) Respon verbal (V) : Berorientasi baik
5
Berbicara mengacau (bingung)
4
Kata-kata tidak teratur
3
Suara tidak jelas
2
Tidak ada
1
GCS 11
: penurunan kesadaran sedang
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korban kemungkina besar hanya mengalami trauma kepala dengan dugaan sebagai berikut: •
Pecahnya pembuluh darah di region frontal kepala (di dahi) akibat terbentur langsung dengan batu sehingga menimbulkan hematoma berukuran 5 cm.
•
Mungkin hanya terdapat komosio serebri (walau korban tidak pingsan) GCS 13-15 (cedera kepala ringan) Dari hasil pemeriksaan pupil (setelah sekitar 4 jam sejak kejadian) tidak didapatkan gejala lateralisasi maupun gejala peningkatan intracranial lain seperti nyeri kepala, mual dan muntah sehingga kemungkinan adanya peningkatan intracranial akibat perdarahan intracranial/kontusio atau edema otak sangat kecil
•
Otak mungkin saja mengalami cedera coup maupun contra-coup Berdasarkan dugaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa GCS korban yang
termasuk ke dalam cedera kepala sedang (9-13) bukan disebabkan oleh trauma kepala yang dialaminya, melainkan cenderung karena intoksikasi zat korosif. Meski hasil pemeriksaan di RSMH hanya menyimpulkan adanya trauma kepala, harus tetap dicurigai adanya fraktur servikal yang perlu dipastikan dengan foto polos leher. Mungkin korban mengalami ekstensi leher yang dapat menyebabkan fraktur akibat dahi yang terbentur batu sedangkan tubuhnya berada dalam posisi tertelungkup.
Mengapa pada kasus terjadi hematom hanya pada region frontal? Karena ia jatuh tertelungkup berarti bagian frontal kepala di bawah.
Bagaimana pembentukan hematomnya?
c. Dampak Trauma Kepala Ketinggian 2 meter tidak terlalu menyebabkan cedera yang parah, diperjelas juga dengan pemeriksaan pupil yang isokor dengan diameter 3 mm dan refleks cahaya +, tetapi kita harus tetap melakukan pemeriksaan kepala (CT Scan atau foto polos kepala) mengingat GCS nya 11 (untuk mengetahui apakah penyebabnya karena adanya cedera kepala sedang atau kekurangan oksigen). Penatalaksanaan awal jika korban mengalami cedera kepala : •
Dekompresi dengan trepanasi sederhana
•
Kompres dengan air dingin
Dari skenario tidak didapatkan data mengenai pertolongan pertama untuk trauma kepala yang di alami pasien, hal ini yang akan mengakibatkan trauma kepala yang dialami pasien dapat menyebabkan komplikasi berupa penurunan kesadaran
5.3. Interpretasi Hasil Pemeriksaan Fisik
Temperatur aksila 37OC Normal 36,5-37,5 OC
Tidak ada gangguan dalam termoregulasi
HR 122x/m Takikardia, akibat pengaktifan saraf simpatis sebagai kompensasi tubuh untuk memenuhi kekurangan O2 akibat penyempitan saluran nafas
TD 130/90 mmHg meningkat Terjadi vasokontriksi akibat kinerja simpatis dan juga penambahan CO akibat peningkatan frekuensi kontraksi jantung
RR 28 x/mnt Meningkat kompensasi tubuh untuk memenuhi kekurangan O2 akibat penyempitan saluran nafas
SpO2 98% Normal (> 95 %)
Disorientasi tempat dan waktu Tidak normal Terjadi penurunan kesadaran Kemungkinan : 1. karena trauma kapitis yang dialaminya yang mengenai daerah frontal,namun perlu pemeriksaan lebih lanjut yakni CT scan. 2. penurunan O2 ke otak.
Pupil isokor diameter 3 mm Normal ,3-5 mm tidak ada lateralisasi
Reflex cahaya + Reflex pupil normal,tidak ada penekanan pada saraf cranial ke 3
Tubuh banyak mengeluarkan keringat Terjadi akibat aktivasi simpatis
Auskultasi dada •
Ronkhi (-)
Normal Tidak ada penumpukan cairan di paru •
Stridor inspirasi (+) Terjadi akibat penyempitan saluran nafas
Ritme jantung takikardi regular kompensasi tubuh untuk memenuhi kekurangan O2 akibat penyempitan saluran nafas
Abdomen dalam batas normal Tidak ada gangguan dalam abdomennya Kemungkinan cairan cuka para belum mengenai area lambung,namun masih sebatas area esophagus
Interpretasi Data Tambahan Hematom regio frontal d=5 cm o ruptur/ pecah pembuluh darah di bagian frontal karena terjatuh dari ketinggian 2 m akumulasi darah di daerah frontal hematoma eritem perioral, dan mukosa mulut o Cuka para (zat korosif) kerusakan pada saluran cerna atas iritasi area perioral (minum dari botol) panas vasodilatasi pembuluh darah dan arteriole kerusakan jaringan pelepasan mediator inflamasi (histamin, bradikinin, serotinin) peningkatan permeabilitas vaskular eritema perioral dan mukosa mulut. retraksi suprasternal o zat korosif dari sal cerna teraspirasi ke saluran pernapasan/ perforasi langsung di esofagus ke laring dan trakea edema mukosa laring obstruksi jalan nafas penurunan aliran udara ke alveolus mekanisme kompensasi untuk mempertahankan ventilasi alveolus penggunaan otot-otot bantu nafas retraksi dinding dada.
bercak eritem dada cuka para tertumpah ke dada iritasi di kulit merusak lapisan kulit eritem dada
5.4. Penegakan Diagnosis Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sudah tertera dalam kasus. Berdasarkan inilah pasien didiagnosis mengalami intoksikasi cuka para dan trauma kepala.
5.5. Patogenesis
5.6. Penatalaksanaan a. Penanganan Awal yang Seharusnya Diberikan di RSUD Sekayu Lakukan Prinsip penanganan pasien gawat darurat: -
Periksa Airway pasien kesulitan bicara (stridor?) buka mulut pasien, bebaskan jalan napas, pasang orofaringeal airway.
-
Periksa Breathing hitung RR pasien, alirkan oksigen melalui orofaringeal airway. Jika breathing tidak membaik, pasang airway definitive, endotracheal tube.
-
Periksa Circulation pasien takikardi reguler, TD 130/90 mmHg, prevensi shock cairan RL 2L.
-
Periksa Disability GCS ketika di RSUD diduga sekitar 14-15, dengan adanya benturan di region frontal, monitor pasien dengan ketat dan segera lakukan CT Scan.
-
Periksa Exposure o Kepala : hematom (d=5) region frontal, eritema perioral dan mukosa mulut o Toraks: jejas (-), eritema (+) o Abdomen: normal o Periksa bagian ekstremitas Bersihkan sisa-sisa cuka para pada perioral dan dada, alirkan cairan (250500 ml). jika terdapat gangguan jalan napas, pemberian susu atau air merupakan kontraindikasi (susu akan mengganggu proses edoskopi, asam sulfat yang dilarutkan dengan air akan menghasilkan panas). Jangan lakukan netralisasi, karena akan menghasilkan panas akibat reaksi eksotermal dari proses netralisasi. Lakukan pemeriksaan endoskopi (dahulukan CT Scan)
-
Pastikan ABC pasien stabil, dan siap dirujuk ke RSMH, monitor vital sign pasien selama perjalanan
b.Penatalaksanaan untuk intoksikasi zat korosif (cuka para) : 1. Pertolongan pertama •
Indentifikasi agen korosif yang tertelan
•
Hindari : -
Penggunaan emetik : sebabkan pajanan berulang
-
Agen penetralisasi : sebabkan injuri termal
-
Bilas lambung : sebabkan perforasi
-
Pertimbangkan NGT
2. Perawatan intensif di UGD :
•
Diprioritaskan – jalur napas dan tanda vital, monitoring jantung segera dan akses intravena.
•
Kontrol jalur napas o
Karena resiko yang sangat cepat dari edema jalur napas, evakuasi segera jalur napas dan kondisi kesadaran. Persiapkan segera alat intubasi endotrakeal dan krikotirotomi. Intubasi orotrakeal atau intubasi dengan bantuan optik fiber lebih baik daripada nasotrakeal untuk mencegah perforasi jaringan lunak
o
Sebisanya, hindari induksi paralisis saat intubasi karena resiko dari distorsi anatomi akibat perdarahan dan nekrosis.
o
Krikotirotomi atau percutaneous needle cricothyrotomy penting dilakukan bila didapat tanda friabilitas ekstrem jaringan atau edema yang signifikan.
•
Pengosongan lambung dan dekontaminasi : o Jangan diberi obat perangsang muntah, cegah re-eksposur dengan agen kaustil o Gastric lavage o NGT suction – spasme dari spingter pilorik mencegah terpaparnya agen terhadap mukosa gaster sampai 90 menit – mencegah terpaparnya intestinal
•
Pemberian cairan intravena.
3. Medikamentosa •
Terapi if
•
Penggunaan kortikosteroid . masih kontroversial, beberapa studi membuktikan efektivitasnya dalam pencegahan striktur. Seperti, metil prednisolon 40-60 mg/hari IV, diberikan setidaknya 3 minggu
•
Antibiotik. Diberikan pada pasien yang menerima terapi steroid di atas. -
Antibiotik – sefalosporin (ceftriaxone) 1-2 gram IV per 24 jam, tidak melebihi 4 g/hari
-
Antibiotik – penisilin dan Beta-lactamase Inhibitor – jika terjadi perforasi
•
PPI – proton pump inhibitor – mencegah terpajannya esofagus yang terluka terhadap asam lambung, yang dapat menyebabkan striktura esofagus
•
Pantoprazole – terapi untuk GER dan esofagitis erosif.
•
Analgesik parenteral, monitor tanda sedasi dan depresi dari respirasi.
4. Follow up •
Pasien yang tidak sengaja tertelan agen penyebab yang asimtomatik dan tidak menunjukkan gejala apapun, boleh dipulangkan 2-4 jam setelah observasi, tak ada kelainan anatomi, pasien harus bisa meminum cairan tanpa kesulitan, tak ada gangguan berbicara
•
NPO (nothing per mouth)
•
Esofagram setelah 3-4 minggu
5. Terapi nutrisi (intake makanan) •
Prinsip : NPO (nothing per mouth) – jangan berikan apapun peroral
•
FEEDING tube o Alat kedokteran yang digunakan untuk pemberian makanan, dikarenakan pasien tidak dapat mengkonsumsi makanan dengan mengunyah o Dinamakan enteral feeding / tube feeding
•
Tipe enteral feeding : o Nasogastrik – dengan selang nasogastrik (nares – esofagus – lambung) o Gastric feeding tube – insersi melalui insisi di abdomen ke lambung (digunakan untuk pemasukan nutrisi enteral jangka panjang. Tipe paling umum adalah percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) tube
•
Efektivitas Dapat digunakan untuk bolus ataupun pemberian makan terus menerus
6. Yang perlu diperhatikan (yang SALAH) : •
Gagal mengevaluasi dan pertolongan jalur napas yang agresif
•
Upaya menetralkan zat yang tertelan dengan asam atau basa lemah
•
Menginduksi muntah – karena dapat membuat esofagus terpajan ulang dengan bahan
•
Asumsi bahwa tidak adanya luka bakar pada orofaring akan menyingkirkan kerusakan jaringan distal
•
Gagal dalam memperoleh data zat/bahan yang tertelan
•
Tidak segera merujuk ke dokter spesialis gastrointestinal / bedah digestif
c. Penatalaksanaan trauma kepala a. Cedera Kepala Ringan (GCS 14-15) •
Riwayat : i. Nama, umur, jenis kelamin, ras, pekerjaan ii. Mekanisme cedera iii. Waktu cedera iv. Tidak sadar segera setelah cedera v. Tingkat kewaspadaan vi. Amnesia : Retrograde, Antegrade vii. Sakit kepala : ringan, sedang, berat
•
Pemeriksaan umum untuk menyingkirkan cedera sistemik
•
Pemeriksaan neurologis terbatas
•
Pemeriksaan rontgen vertebra servikal dan lainnya sesuai indikasi
•
Pemeriksaan CT scan kepala sangat ideal pada setiap penderita kecuali bila memang sama sekali asimtomatik dan pemeriksaan neurologis normal
•
Observasi atau dirawat di RS jika : i. CT scan tidak ada ii. CT scan abnormal iii. Semua cedera tembus iv. Riwayat hilang kesadaran v. Kesadaran menurun vi. Sakit kepala sedang- berat vii. Intoksikasi alcohol/obat-obatan viii. Kebocoran likuor : Rhinorea-otorea ix. Cedera penyerta yang bermakna x. Tak ada keluarga di rumah xi. GCS < 15 xii. Defisit neurologis fokal
b. Cedera Kepala Sedang (GCS 9-13) •
Sama dengan untuk cedera kepala ringan ditambah pemeriksaan darah sederhana
•
Pemeriksaan CT scan kepala pada semua kasus
•
Setelah dirawat : i. Pemeriksaan neurologis periodic
ii. Pemeriksaan CT scan ulang bila kondisi penderita memburuk atau bila penderita akan dipulangkan c. Cedera Kepala Berat (GCS <8) •
Periksa ABCDE
•
Primary Survey dan resusitasi
•
Secondary Survey dan riwayat AMPLE
•
Reevaluasi neurologis : GCS i. Respon buka mata ii. Respon motorik iii. Respon verbal iv. Respon cahaya pupil
•
Obat-obatan : i. Manitol ii. Hiperventilasi sedang (PCO2 <35mmHg) iii. Antikonvulsan
•
Tes Diagnostik (sesuai urutan): i. CT scan ii. Ventrikulografi udara iii. Angiogram
5.7. Komplikasi dan Prognosis 1. Prognosis
Dubia. Tergantung dari derajat kerusakan jaringan, lama waktu terpajan dan sifat fisik dari agen (termasuk pH, volume, dan konsentrasi; kemampuan penetrasi jaringan, dan titration reserve (jumlah jaringan yang dibutuhkan untuk menetralisir agen) 2. Komplikasi
Edema jalan napas atau obstruksi
Striktur esofagus
Perforasi dari gastroesofagus o Komplikasi sekundernya termasuk : mediastinitis, perikarditis, pleuritis, pembentukan fistula trakeoesofagal, pembentukan fistula esofagal-aortic, dan peritonitis o Perforasi dapat terjadi 4 hari setelah terpapar zat asam. o Obstruksi dari saluran gaster setelah 3-4 minggu terpajan o Hemorhagik pada regio gastrointestinal secara akut o Perdarahan dari traktus gastrointestinal
Resiko jangka panjang, squamous cell carcinoma, ca esofagus 1-4% kasus.
3. Kompetensi Dokter Umum Kompetensi dokter umum untuk trauma kepala dan keracunan adalah 3B, yaitu mampu membuat diagnosis berdasarkan pemeriksaan fisik dan tambahan, dapat memutuskan dan memberikan terapi awal, serta merujuk ke spesialis yang relevan pada kasus gawat darurat. Untuk kasus Gawat darurat (dalam kasus ini), dokter rumah sakit harus melakukan tatalaksana sampai kondisi pasien stabil